Fenomena ”post truth” dan meredupnya kepakaran seiring munculnya alternatif informasi di ruang publik jadi tantangan berat bagi bangsa. Pada hakikatnya, ini tantangan Maarif Institute juga lembaga-lembaga lainnya.
Pada 28 Februari 2023, Maarif Institute, lembaga yang concern terhadap isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan genap memasuki perjalanan dua dekade. Sejak awal berdiri, Maarif Institute secara kultural berkomitmen menjadi salah satu tenda bangsa yang bergerak untuk kerja-kerja kemanusiaan, merawat kebinekaan, mendorong penegakan hak asasi manusia, memperjuangkan kebebasan beragama, mengampanyekan watak dan ciri khas Islam Indonesia sebagai agama rahmatan lil alamin, inklusif, toleran, egaliter dan nondiskriminatif, yang memiliki kesesuaian dengan demokrasi yang berpihak kepada keadilan sosial, sebagaimana dicita-citakan Buya Syafii Maarif.
Apa yang telah dilakukan Maarif Institute selama dua dekade tidak lain merupakan ikhtiar bersama untuk merealisasikan gagasan besar Buya Syafii yang terangkum dalam konsep keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Setelah wafatnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bisa dikatakan Buya Syafii merupakan sosok dari sedikit tokoh yang mampu mewarnai diskursus terkait isu-isu kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan.
Baca Juga: Warisan Buya Syafii Maarif untuk Indonesia
Sepanjang perjalanan karier intelektualnya, Buya Syafii tak pernah absen dari ruang-ruang kelas keindonesiaan, keislaman, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, Buya Syafii selalu konsisten menyuarakan kebenaran dan keadilan, gigih menyuarakan pengamalan Pancasila secara otentik, menegaskan pentingnya anak-anak bangsa untuk menjalin persaudaraan, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik intra maupun antar-agama, menuntun manusia menapaki langkah demi langkah agar mengenali ajaran agama sebagai panggilan kemanusiaan.
Kegelisahannya atas pelbagai persoalan bangsa dan keterlibatannya secara langsung sejalan dengan konsep ”Intelektual Organik” yang digagas Antonio Gramsci. Pada diri Buya Syafii melekat karakter sebagai man of idea sekaligus sebagai man of action.
Matinya kepakaran
Berbeda dengan Cak Nur dan Gus Dur yang lebih dahulu meninggalkan kita, Buya Syafii yang wafat tahun lalu masih mengalami hidup di era teknologi dan keterbukaan informasi di mana masyarakat bisa beropini atau menyuarakan pendapatnya dengan bebas, serta dapat memproduksi berita dan membentuk opini melalui platform media sosial.
Era saat berbagai layanan informasi dan aplikasi internet, baik dari sumber yang jelas maupun anonim, tidak jarang bernada provokatif dan menyesatkan. Namun, anehnya, berita-berita bohong bernada provokatif yang berpotensi memecah-belah umat inilah yang justru banyak diikuti dan dipercaya dibandingkan dengan pandangan pakar.
Orang seperti Buya Syafii yang punya integritas moral yang tinggi bisa menjadi korban bully (perundungan) untuk sikap pilihan berdasarkan prinsip-prinsip kokoh yang dimiliki. Berbagai cacian, hinaan, bahkan sampai hujatan yang tidak pernah dilakukannya pun menjadi makanan harian.
Namun, agaknya, Buya tidak hirau dengan persetujuan atau perlawanan. Yang ia pedulikan adalah orang harus jujur pada hati nuraninya sendiri, bersikap adil kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang tidak kita sukai. Hingga di usia senjanya, Buya tak surut dan berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan. Justru volumenya semakin kuat.
Sepeninggal Buya Syafii, Gus Dur, dan Cak Nur, bangsa besar ini tentu membutuhkan otoritas pakar atau figur yang memiliki kepedulian terhadap kaum minoritas yang terpinggirkan, menghadirkan keadilan sosial.
Di era post truth, orang tidak lagi mempercayai fakta-fakta obyektif, tetapi merujuk sesuatu yang didasarkan atas kepercayaan yang tidak didukung fakta. Fenomena post truth dan meredupnya kepakaran seiring menyeruaknya berbagai alternatif informasi di ruang-ruang publik menjadi tantangan berat bagi bangsa—yang pada hakikatnya menjadi tantangan bagi Maarif Institute serta lembaga-lembaga lain yang punya perhatian yang sama terhadap isu-isu kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan.
Sepeninggal Buya Syafii, Gus Dur, dan Cak Nur, bangsa besar ini tentu membutuhkan otoritas pakar atau figur yang memiliki kepedulian terhadap kaum minoritas yang terpinggirkan, menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini tidak tersapa, serta mampu merespons persoalan ekonomi dan politik yang berkembang.
Meredupnya kepakaran sejatinya adalah cerminan perilaku kita saat ini di dunia maya. Adanya kelas sosial baru yang dicirikan dengan kebebalan dan bicara tanpa otoritas keilmuan yang memadai, dialog publik yang tidak memiliki ketelitian intelektual, serta banyaknya orang awam yang mengabaikan fakta, namun berani ’ugal-ugalan’ menyerupai para pakar. Namun, hebatnya, mereka dapat menggerakkan dan membentuk ruang publik kita.
Krisis intelektual organik
Berhadapan dengan kenyataan yang cukup mencemaskan ini, akhirnya kita berharap akan hadirnya intelektual-intelektual organik di negeri ini. Konsep intelektual organik ini sendiri sebenarnya dicetuskan oleh Antonio Gramsci.
Gramsci (1999), menilai bahwa peran intelektual sangat penting sebagai bagian dari suprastruktur. Mereka merupakan suatu kelompok sosial yang otonom dan independen. Dalam dunia suprastruktur, kaum intelektual menampilkan fungsi organisasional dan konektif di dalam wilayah masyarakat sipil.
Figur intelektual organik yang mampu merasakan denyut emosi, semangat, dan apa yang dirasakan oleh kaum papa, serta memihak kepada mereka masih sangatlah langka. Selama ini makna intelektual lebih dipahami secara tradisional yang lekat kaitannya dengan profesi, seperti dosen, guru, ilmuwan, peneliti, dan hanya dipahami sebatas sebagai ’orang yang gemar berwacana tanpa melakukan aksi-aksi nyata’.
Para akademisi di lembaga-lembaga pendidikan bagaikan mesin; memproduksi—jika tak boleh dikatakan ”menghamba”—kepada karya ilmiah, jurnal internasional untuk kepentingan pragmatis kenaikan pangkat dan jabatan. Mereka disibukkan dengan standar sistem penilaian kualitas intelektual yang terlalu administratif dan birokratis dibandingkan menjadi sebagai seorang pemikir yang penuh risiko.
Baca Juga: Identitas dan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan
Jika pun mereka memantik kesadaran, itu hanya sebatas berhenti di ruang-ruang kelas, di ruang seminar dan pelatihan, tanpa kemudian mendorong keadaran dan memicu masyarakat luas untuk melakukan aksi-aksi nyata. Kesadaran kritis di ruang-ruang tersebut pada akhirnya menjadi kerupuk dalam ruang terbuka yang lama-lama melempem. Masalah lain yang membuat gerakan-gerakan menjadi tidak masif adalah karena jarak keterhubungan antara intelektual dan masyarakat sangatlah jauh.
Intelektual dalam pengertian tradisional ini biasanya menempati posisi-posisi strategis di ruang lingkup pemerintahan yang secara posisi turut diuntungkan dengan adanya agenda penguasa, misalnya hibah proyek, janji kenaikan pangkat, jaminan tunjangan gaji, dan keuntungan-keuntungan materi lainnya. Maka, tidaklah mengherankan jika di kemudian hari ada akademisi yang turut membenarkan kebijakan-kebijakan bermasalah yang merugikan masyarakat luas, tetapi menguntungkan kelompok oligarki yang sedang berkuasa.
Menurut Robert Brym (1993), intelektual adalah orang-orang yang karena pekerjaannya terutama terlibat dalam produksi ide-ide. Ide-ide ini kemudian membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Mereka ini tidak terikat kepada kepentingan tententu, independen dan otonom untuk menyatakan kebenaran, serta mampu mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat sipil sebagai bentuk penyadaran.
Sebagai lembaga yang concern terhadap isu-isu agama dan sosial-kemasyarakatan, Maarif Institute, yang kini menapaki usia yang ke-20 tahun, masih harus bekerja keras lagi untuk merawat keindonesiaan dengan cara membangun kerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai visi yang sama, terlibat dan bertumbuh kembang dalam permasalahan bangsa, menciptakan solusi serta membangkitkan kesadaran kritis untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.
Baca Juga: Catatan tentang Keadilan Sosial
Terakhir, ruang publik memiliki peran lebih besar dengan membuka pandangan, bersikap obyektif terhadap suatu permasalahan, menghindari bias informasi, dan menerima masukan dari para pakar. Hal yang tak kalah penting adalah menunda kematian kepakaran hanya mungkin dilakukan jika peran intelektual organik mampu memosisikan diri sebagai pembebas.
Moh Shofan, Direktur Program Maarif Institute
sumber:
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/26/dua-dasawarsa-maarif-institute-dan-tantangan-era-media

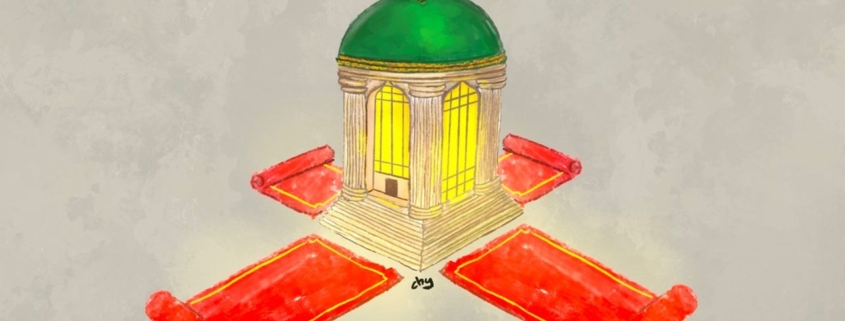



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!