Bayangkan, seorang tahanan Ahmad Husein berani menyela pembicaraan Bung Karno yang pada saat itu sedang berkuasa penuh, dikelilingi oleh para pejabat tinggi negara, termasuk Jenderal Yani yang memerintahkan mengebom Painan tahun 1958 itu. Bukankah panorama ini sekaligus menujukkan bahwa asli keminangan Ahmad Husein masih bertahan, sekalipun datang dari sel tahanan? Sungguh keberanian Husein ini sesuatu yang luar biasa.
Reaksi Bung Karno “Jiamput, lu!” telah mencairkan suasana dan menghilangkan kegelisahan Ahmad Husein, si Minang, sampai batas yang sangat jauh. Saya tidak tahu, setelah hampir setengah abad berlalu pasca PRRI, apakah jiwa merdeka itu masih bertahan atau telah larut dalam kubangan sub-budaya pragmatisme materialistik sebagai bagian dari budaya Indonesia yang sedang jatuh. Apakah demi pragmatisme jangka pendek, si Minang kontemporer masih menjadi pewaris Tan Malaka atau telah berlaku ungkapan ini tanpa reserve: “Bialah kapalo bakubang asa tanduak lai manganai?”
Saya katakan tanpa reserve karena sering kali parameter moral dan etika sudah tidak berfungsi lagi. Orang sudah berenang dalam limbah mumpungisme tanpa hirau batas dan pematang. Kabarnya konon, di Minang sekarang, ungkapan-ungkapan “sakti” seperti: “adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; syarak mangato, adaik mamakai” plus petatah-petitih, gurindam, dan sebagainya yang sarat makna itu sudah agak lumpuh tak berdaya, telah dijadikan retorika murahan tanpa ada bukti dalam kenyataan dan pergaulan sehari-hari.
“Fabrik Kearifan” ini sudah berubah menjadi “Fabrik Komersial,” uang telah menjadi “agama” ditingkahi khotbah para khatib Jum’at yang kehabisan energi dan kosa-kata. Untuk kota-kota besar, polusi suara keras yang diputar via kaset sopir para angkot telah semakin menyempurnakan krisis budaya yang berdimesi banyak itu. Saya gagal memahami mengapa para sopir itu tidak lagi menghargai telinga manusia yang masih normal. Alangkah manisnya jika lagu-lagu yang diputar itu dengan suara yang lebih beradab.
Situasi semakin menjadi parah pada saat politik sedang menjadi mata pencarian, karena lapangan kerja sulit sekali. Lautan pengangguran terbentang di berbagai pojok tanah air. Lagi-lagi Minang sedang memosisikan diri sebagai Indonesia mini dalam formatnya yang sempurna. Apakah ini akibat trauma PRRI plus kemudian merajalelanya PKI di Minangkabau setelah PRRI dikalahkan tahun 1960-an? Tidak cukup itu.
Dengan UU No 5/1979 yang memecah nagari menjadi desa telah membuyarkan basis kultural Minang pada tingkat yang paling bawah. Nagari yang semula berjumlah 543 disunglap menjadi desa dengan jumlah 3500, sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Pada era otoritarian itu, lembaga adat seperti LKAAM terpecah di antara yang mendukung dan ragu-ragu. Dengan kenyataan ini, masyarakat di akar rumput menjadi berserakan, tidak ada lagi tali pengikat kultural yang berwibawa. Sekalipun sekarang nagari telah mulai difungsikan kembali, keadaannya masih pada tahap masa transisi yang tidak mudah.
Gejala lain yang pernah disampaikan kepada saya oleh perantau adalah jika dulu orang Minang umumnya hampir tidak ada yang gila kuasa. Puncaknya di panggung nasional terlihat, misalnya, pada sikap Hatta, Sjahrir, Assaat, Natsir, yang dengan mudah dan enteng saja melepaska jabatan. Tetapi kabarnya sekarang perubahan drastis sedang berlaku.
Orang Minang jika sudah berada dalam posisi tertentu, apalagi jika posisi itu menguntungkan secara materi dan gengsi, mereka akan mempertahankannya mati-matian dengan segala cara. Saya tidak tahu apakah gejala ini sudah merupakan gelombang besar atau hanya sekadar riak-riak kecil yang tidak terlalu signifikan untuk dicemaskan.
Tentu budaya tak hirau kuasa ini ada plus-minusnya. Plusnya akan terlihat bahwa orang Minang sangat peduli dengan prinsip moral dan etika, kekuasaan bukan tujuan, tetapi sekadar alat untuk menegakkan kesalehan sosial; minusnya, orang lain yang belum tentu baik akan dengan cepat merebut posisi itu.
Jika ini yang terjadi, publik akan mengalami kerugian besar, sebab pengganti si Minang ternyata cacat secara moral. Oleh sebab itu, ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, banyak anak muda yang menyayangkan. Sebab, ibarat gas dan rem pada mobil, sepeninggal Hatta, Sukarno sebagai gas tidak bisa direm lagi. Setelah Hatta sebagai benteng demokrasi berada di luar sistem, Sukarno yang dibantu partai-partai tertentu dalam tempo tidak lama dengan mudah mengubur sistem politik egalitarian ini. Rezim Orde Baru hanyalah meneruskan sistem anti-demokrasi ini.

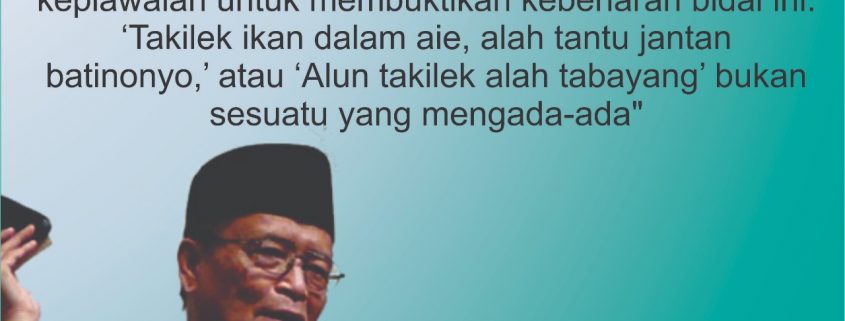

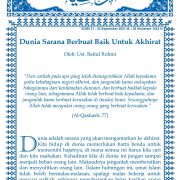



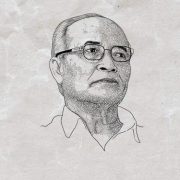



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!