Istilah “bencana budaya” bukan berasal dari saya, tetapi dari seorang sastrawan Minang yang setia menetap di Padang, seperti pendahulunya almarhum A.A. Navis yang di akhir hayatnya juga telah menjadi sahabat saya. Judul “Ranah Gurindam” jika disempurnakan menjadi “Ranah Gurindam, Petatah-Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, dan Sya’ir,” tetapi agar tidak terlalu panjang, saya singkatkan saja dalam kemasan “Ranah Gurindam,” di samping terasa lebih manis dan sedikit puitis.
Sebagai seorang yang bukan sastrawan, dalam orasi ini nanti sudah barang tentu akan banyak ditemui ungkapan-ungkapan yang kurang pas dan kurang sedap di telinga orang Minang yang memiliki modal budaya yang sangat kaya itu. Beberapa minggu yang lalu, di kantor Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, ketika saya sampaikan rencana pertemuan budaya ini kepada Rosihan Anwar, kontan dijawab: “Saya tidak berani.”
Jika seorang sastrawan dan wartawan kawakan sekaliber Rosihan Anwar, angkatan Chairil Anwar dan Asrul Sani, tidak berani bicara budaya Minang, pertanyaannya adalah: mengapa saya berani? Jawabannya singkat dan sederhana: karena saya bukan sastrawan dan bukan budayawan, paling tinggi posisi saya adalah seorang peminat, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan posisi yang seperti ini, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu yang sudah lama terasa di hati, terpendam di fikiran, dan terngiang di angan, tentang Minangkabau kontemporer dengan segala permasalahannya yang berdimensi banyak.
Minangkabau dan Indonesia: Sebuah Kegalauan Budaya
Sebagai seorang yang berasal dari nagari tersuruk, Sumpur Kudus, saya sudah merantau sejak usia 18 tahun. Barangkali saya sudah tidak begitu akrab lagi dengan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang masih setia menetap di kawasan yang dikenal sebagai “Fabrik Kearifan Kata” yang kaya. Oleh sebab itu, saya hanya akan memberikan kesan secara umum dan selintas saja tentang Minangkabau sekarang.
Terlihat dan terasa oleh saya bahwa Minangkabau atau ranah Minang dalam perspektif budaya sudah menjadi bagian dari Indonesia yang sedang bingung merumuskan jati-dirinya di tengah-tengah peluang dan ancaman globalisasi yang tidak mengenal rasa iba. Indonesia sebagai bangsa dan negara muda, karena kelalaian para pemimpin sejak proklamasi 1945 sampai detik ini, masih tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menjaga kedaulatannya yang telah agak lama dilecehkan oleh negara-negara jiran seperti Singapura dan Malaysia.
Dengan penduduk sekitar 240 juta dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 24 juta dan Singapura lima juta, Indonesia adalah ibarat gajah setengah lumpuh. Telinga dan sela-sela jari kakinya dimasuki berbagai jenis semut kecil-kecil yang ganas, sehingga menyebabkan si gajah menjadi gelisah dan tidak percaya diri.
Semut-semut ini berupa manuver-manuver kecil dari Malaysia dan Singapura, dua negara jiran yang lagi bermaya secara ekonomi. Mereka tahu betul bahwa Indonesia sedang sakit yang agak parah. Mereka sedang mengukur Indonesia sampai di mana daya tahannya. Hutan yang 2/3 luasnya sudah gundul semakin menyulitkan posisi Indonesia untuk angkat kepala dalam berbagai pertemuan dunia.
Tetapi apakah benar negeri-negeri jiran ini ingin melihat Indonesia semakin lemah? Dalam pembicaraan saya dengan para diplomat dari Malaysia, Singapura, dan Brunei dalam berbagai kesempatan, mereka sebenarnya tidaklah menginginkan Indonesia jatuh, tetapi tetap tegak utuh sebagai bangsa yang kuat. Sebab jika Indonesia goyang dan labil, maka keseimbangan geo-politik di kawasan Asia Tenggara akan mengalami kegoncangan dahsyat yang tak terbayangkan akibatnya. Oleh sebab, itu semestinya “semut-semut” jiran itu dijinakkan satu persatu melalui kemampuan diplomasi dengan kualitas super tinggi. Dalam diplomasi inilah kita sering benar kedodoran.
Sebagai bangsa yang lagi “gerah” dengan masalah domestik yang berketiakular, Indonesia sekarang memang tidak memiliki kemampuan diplomasi yang tangguh dan meyakinkan, seperti dulu pernah diperlihatkan Agus Salim, Hatta, Sjahrir, Roem, L.N. Palar, Adam Malik, Soedjatmoko, Mochtar Kusumaatmadja, dan masih ada nama-nama lain. Ada semacam kekosongan di ruang diplomasi ini karena banyak dihuni oleh birokrat yang bekerja umumnya secara mekanis dan tunggu perintah.
Dunia diplomasi adalah dunia silat lidah yang sangat sesuai dengan bakat anak bangsa yang berasal dari “Ranah Bidal dan Gurindam.” Lingkungan kultur Minang asli merupakan modal utama untuk berdebat dengan penuh percaya diri di fora dunia dalam upaya membela martabat bangsa ini dari segala pelecehan dan pencibiran yang dilakukan pihak lain.
Dengan modal kultur Minang asli yang dikembangkan lebih jauh melalui interaksi aktif dan kreatif dengan kultur bangsa-bangsa lain, maka kepiawaian untuk membuktikan kebenaran bidal ini: “Takilek ikan dalam aie, alah tantu jantan batinonyo,” atau “Alun takilek alah tabayang” bukan sesuatu yang mengada-ada, sekalipun dikemas dalam format yang agak berlebihan. Memang sebagian orang Minang suka melebih-lebihkan, agar terlihat hebat dan keren, sekalipun kadang-kadang jauh dari kenyataan.
Saya harus menekankan keaslian Minang, sebagaimana yang tersurat dan terbaca dalam kumpulan gurindam, petatah-petitih, mamang, bidal, dan pantun yang sangat impresif. Keaslian yang dikawinkan dengan unsur budaya rantau inilah yang melahirkan Agus Salim, Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Yamin, Adinegoro, Natsir, Hamka untuk “bersilat lidah” di fora nasional atau internasional.
Tetapi harus dicatat pula seorang Tan Malaka jika tetap terbenam di nagari Pandan Gadang, Suliki, tentu ia tidak akan pernah menjadi salah seorang tokoh komintern tahun 1920-an, sekalipun kemudian “bentrok” dengan Stalin, sang diktatur. Jika tidak beranjak dari Pandan Gadang, Tan Malaka paling-paling menjadi camat atau bupati Limo Puluah Koto.
Dengan latar keminangannya, Tan Malaka tidak pernah kehilangan watak merdekanya di bumi mana pun ia berada, dengan siapa pun ia berhadapan, karena menurut catatan Hatta, Tan Malaka “tidak mempunyai tulang punggung yang mudah membungkuk,” persis seperti diajarkan oleh warisan budaya Minang asli, khususnya yang terdapat dalam sub-kultur Bodi Caniago yang sarat dengan nilai-nilai egalitarian dan demokrasi. “Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakek” adalah bagian dari pesan egalitarian itu.
Sisa dari jiwa merdeka itu masih dimiliki oleh tokoh Dewan Banteng Ahmad Husein, saat dipanggil Presiden Sukarno akhir 1961. Inilah suasana dalam dialog itu:
Akhir 1961. Ahmad Husein gelisah ketika ke selnya, di Rumah Tahanan Militer, Jakarta Pusat, datang Kolonel Suparman. Ia diperintahkan menghadap Bung Karno di Istana Bogor. Husein menyangka inilah saatnya ia betul-betul disingkirkan.
Setiba dia di Istana, Bung Karno sudah dikelilingi Perdana Menteri Djuanda Kertawidjaja, Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, Menteri Pembangunan Chairul Saleh, dan Jenderal Ahmad Yani. Pembicaraan seputar PRRI.
“Don’t talk about that anaymore,” Bung Karno menyergah. “Itu peristiwa sejarah yang pasti terjadi walaupun Ahmad Husein tidak dilahirkan di Indonesia atau tidak ada di Indonesia., dan ini proses sejarah. Tak ada satu kekuatan yang dapat menghambat atau menghalanginya.”
“Kalau saya memberontak, Pak,” Husein menimpali, “bukan kehendak saya memberontak, tapi Bapak yang menyuruh saya.”
“Lo, kok kamu bilang saya yang menyuruh?”
“Ingatkah Bapak, pada tahun 1958 bulan Januari, Bapak berpidato di Surabaya: ‘Kalau saya pemuda, saya akan berontak terhadap keadaan ini.’”
“Jiamput, lu!” Bagi saya, dialog ini bernilai sejarah bila dikaitkan dengan kultur Minang yang mendidik manusia menjadi merdeka yang dengan kepala tegak menghadapi kenyataan, betapa pun mungkin pahit dan penuh risiko. Nilai kemerdekaan itu masih belum hilang dari diri Ahmad Husein.

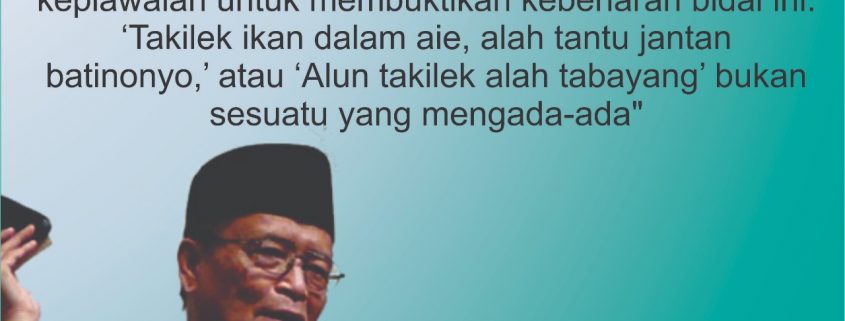
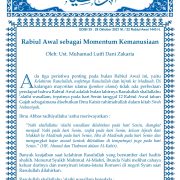



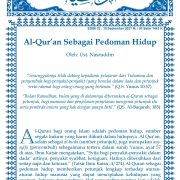


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!